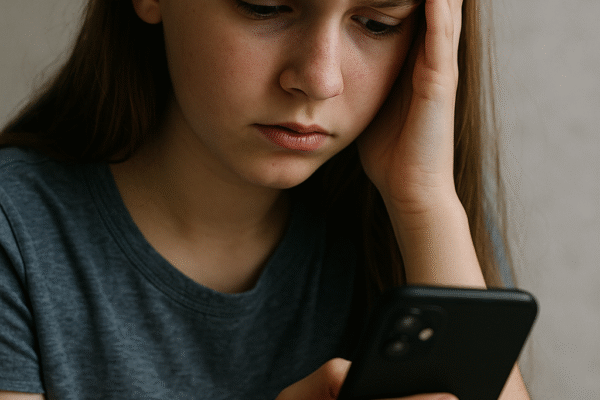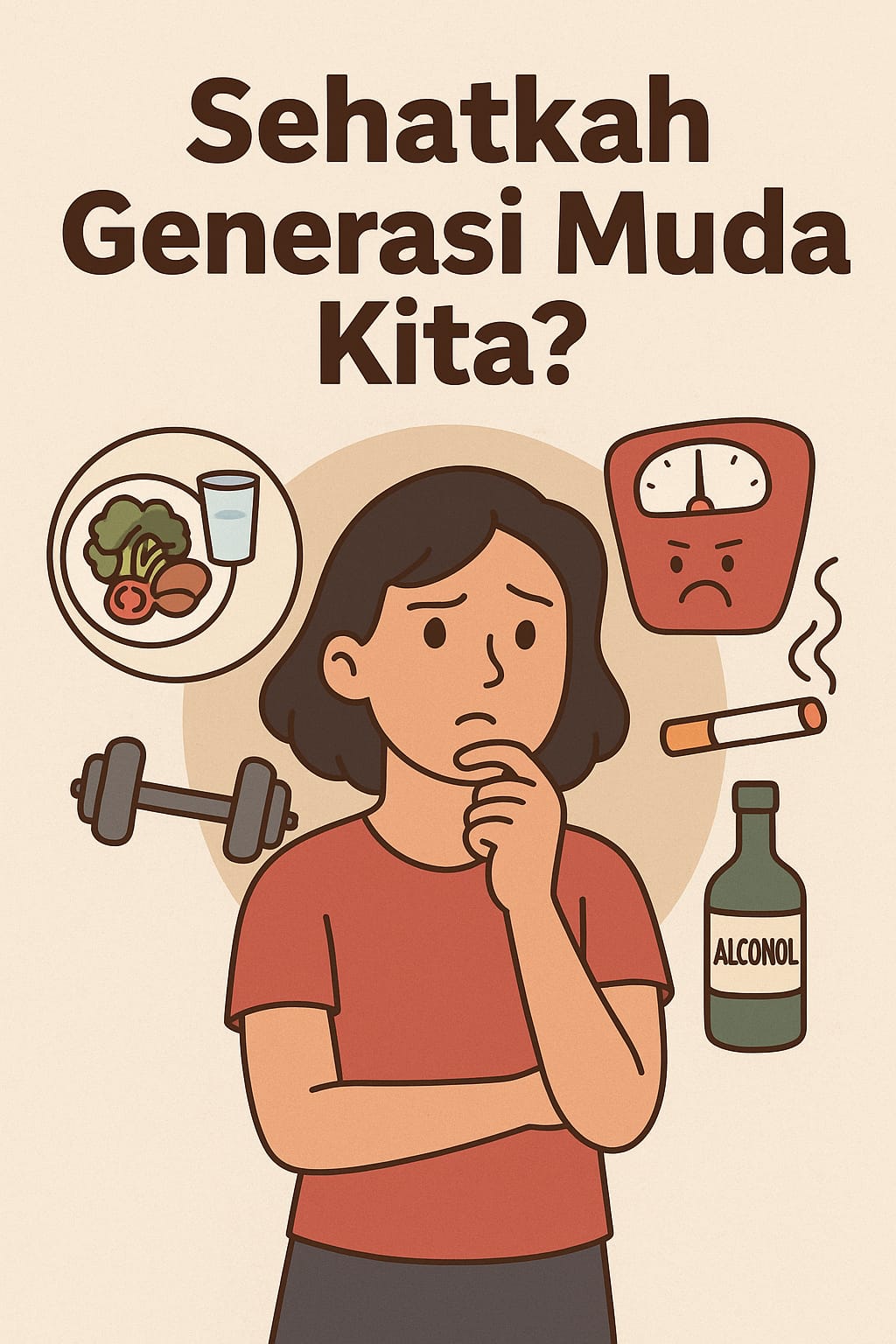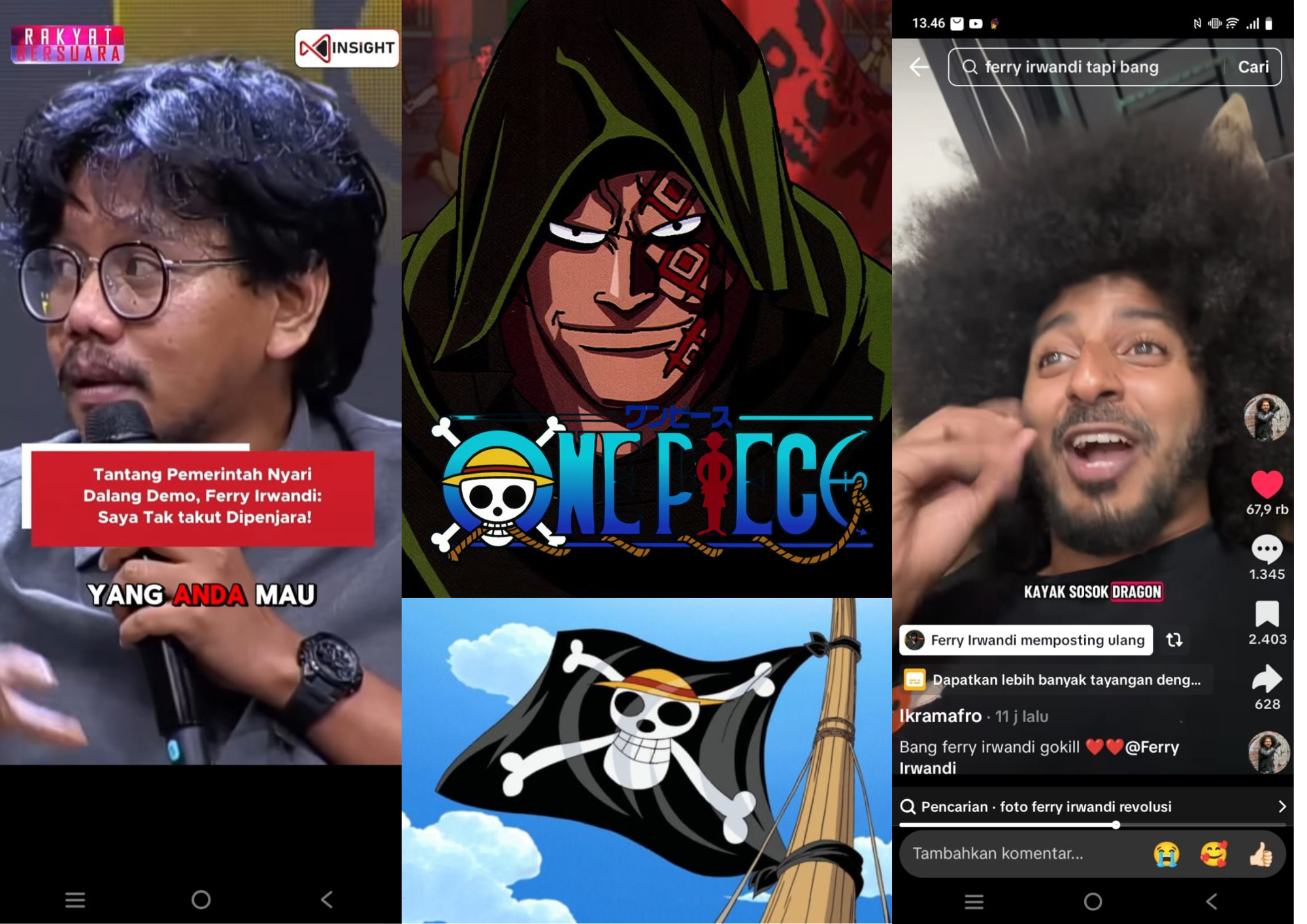Oleh: Nanda Rizki
Di tengah dinamika demokrasi Indonesia, aksi massa kerap menjadi medium bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi politik maupun sosial. Demonstrasi di berbagai kota, mulai dari Jakarta, Malang, hingga Solo, seringkali merefleksikan kegelisahan publik terhadap kebijakan negara. Namun, dalam setiap gelombang protes, yang seharusnya dijaga adalah rasa kemanusiaan. Sayangnya, hal itu justru sering dikesampingkan. Fenomena represifitas aparat terhadap tenaga medis yang bertugas di lapangan menjadi bukti nyata bahwa kemanusiaan kerap terpinggirkan dalam pengelolaan keamanan.
Tenaga medis memiliki posisi yang sangat jelas: mereka adalah pihak netral. Tidak peduli siapa yang terluka—peserta aksi, aparat, maupun masyarakat sipil yang kebetulan berada di lokasi—mereka tetap hadir untuk memberikan pertolongan. Namun dalam sejumlah peristiwa, tenaga medis justru menjadi korban kekerasan aparat. Ambulans dihadang, pos medis dirusak, relawan dipukul, bahkan ada yang diancam akan dibunuh. Tindakan semacam ini tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga merusak fondasi kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi.
Pertanyaan fundamental pun muncul: mengapa pihak medis yang jelas-jelas tidak memiliki kepentingan politik, bahkan hanya bertugas memberikan bantuan, justru diperlakukan sebagai ancaman? Apakah negara gagal memahami peran vital medis dalam menjaga nyawa manusia di tengah situasi genting? Atau memang ada budaya represif yang telah mengakar dalam tubuh aparat sehingga mereka sulit membedakan antara ancaman nyata dengan pihak penolong?
Tulisan ini hendak mengupas persoalan tersebut dengan menyoroti sejumlah kasus represifitas aparat terhadap tenaga medis, meninjau payung hukum yang seharusnya melindungi mereka, serta memberikan catatan kritis terhadap absennya evaluasi dari pihak berwenang.
Represifitas aparat terhadap medis bukanlah isu baru. Dalam setiap gelombang demonstrasi besar, laporan mengenai gangguan terhadap tim medis hampir selalu muncul. Padahal, peran tenaga medis di tengah aksi massa sangat vital. Mereka berfungsi sebagai garda kemanusiaan, memastikan bahwa siapapun yang menjadi korban—baik karena kelelahan, sesak napas akibat gas air mata, maupun luka fisik akibat bentrokan—dapat segera mendapatkan pertolongan.
Sayangnya, alih-alih dilindungi, mereka justru sering diperlakukan sebaliknya. Berbagai catatan menunjukkan bahwa represifitas ini bukan kejadian sekali-dua kali, melainkan pola yang terus berulang. Artinya, ada persoalan serius dalam cara aparat memandang keberadaan medis. Alih-alih dihormati, mereka dianggap bagian dari kelompok demonstran yang harus ditundukkan.
Lebih ironis lagi, dalam sejumlah kasus, tidak ada evaluasi berarti dari pihak aparat. Alih-alih mengakui kesalahan dan memperbaiki mekanisme pengamanan, kasus-kasus serupa justru terulang. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa tindakan represif bukanlah insiden semata, melainkan bagian dari budaya kekerasan yang dilegitimasi dalam praktik pengendalian massa.
Kasus-Kasus Represifitas terhadap Medis
Untuk memahami persoalan ini secara lebih jelas, perlu melihat contoh-contoh konkret represifitas aparat terhadap tenaga medis dalam beberapa tahun terakhir. Kasus-kasus ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana aparat gagal menghormati posisi netral tenaga kesehatan.
Solo, 29 Agustus 2025. Di Jalan Slamet Riyadi, Dika, seorang sopir ambulans, mengalami pemukulan oleh aparat ketika berusaha menjalankan tugasnya. Ambulans yang seharusnya diberi akses prioritas justru menjadi sasaran kekerasan. Pada hari yang sama, Raditya Baga, seorang relawan medis yang mengawal ambulans, juga menjadi korban tindakan represif aparat. Peristiwa ini menegaskan bahwa bahkan di tengah situasi darurat medis, aparat lebih memilih menggunakan kekerasan daripada memberikan perlindungan.
Jakarta, demonstrasi besar menolak RUU TNI. Di ibu kota, tenaga medis tidak luput dari tindakan represif. Saat berusaha menolong massa aksi yang terkena dampak gas air mata, tim medis justru dihalangi aparat. Lebih parah lagi, akses ambulans menuju rumah sakit tidak diberikan jalan. Kejadian ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan dan hukum positif.
Malang, 23 Maret 2025 (Demo RUU TNI). Peristiwa di Malang menjadi salah satu catatan kelam. Pos medis yang seharusnya menjadi ruang aman malah dirusak oleh aparat. Relawan medis mendapat ancaman pembunuhan, sebuah tindakan ekstrem yang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Alih-alih melindungi, aparat justru memperlakukan tim medis sebagai musuh.
Agustus 2024, demo RUU Pilkada. Ketika tim medis hendak masuk ke area kampus untuk memberikan bantuan, mereka dihadang oleh aparat. Penolakan semacam ini berpotensi memperburuk kondisi korban luka, karena keterlambatan pertolongan dapat berdampak fatal.
Berbagai kasus di atas menggambarkan pola represifitas yang konsisten. Medis yang seharusnya dilindungi, justru selalu menjadi korban. Pola ini jelas menyalahi prinsip dasar perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang diakui baik secara nasional maupun internasional.
Analisis Represifitas
Ada beberapa hal yang bisa dicermati dari pola represifitas ini. Pertama, ada kecenderungan aparat untuk menyamaratakan semua pihak di lokasi demonstrasi sebagai ancaman. Dalam kerangka pikir seperti ini, kehadiran medis pun dianggap tidak berbeda dengan massa aksi. Padahal, fungsi medis adalah kemanusiaan, bukan politik.
Kedua, tindakan represif terhadap medis menunjukkan kegagalan aparat dalam membedakan peran. Manajemen keamanan yang seharusnya menjamin keselamatan semua pihak justru berubah menjadi instrumen ketakutan. Kekerasan terhadap tenaga medis tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Ketiga, dampaknya jauh lebih luas. Dengan adanya intimidasi, ancaman, hingga kekerasan terhadap tenaga medis, banyak relawan menjadi enggan terlibat dalam aksi-aksi selanjutnya. Padahal, keberadaan mereka sangat vital dalam mengurangi risiko korban jiwa. Tanpa medis, aksi massa yang diwarnai bentrokan berpotensi menghadirkan lebih banyak tragedi.
Dengan demikian, represifitas terhadap medis bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang mengancam nyawa.
Payung Hukum yang Dilanggar
Secara normatif, ada landasan hukum yang jelas mengenai perlindungan terhadap tenaga medis. Baik hukum internasional maupun hukum nasional menegaskan bahwa tenaga kesehatan wajib dihormati dan dilindungi.
Dalam kerangka hukum internasional, Protokol I 1977 ayat 12 paragraf 1 menyatakan bahwa unit kesehatan harus selalu dihormati dan dilindungi, serta tidak boleh dijadikan sasaran perang. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam situasi konflik bersenjata sekalipun, tenaga medis tetap memiliki perlindungan khusus. Maka dalam konteks demonstrasi sipil, seharusnya perlindungan ini lebih mudah dijamin.
Di tingkat nasional, Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, khususnya Pasal 57 ayat 4, menegaskan bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Ketentuan ini jelas menolak segala bentuk kekerasan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap tenaga kesehatan.
Dengan demikian, represifitas aparat terhadap medis tidak hanya bertentangan dengan nilai moral, tetapi juga melanggar hukum. Aparat yang seharusnya menjadi penegak hukum justru menjadi pelanggarnya.
Kurangnya Evaluasi Aparat
Meski kasus-kasus represifitas terhadap medis terus berulang, evaluasi nyata dari pihak aparat tampaknya minim. Tidak ada laporan publik yang menunjukkan adanya investigasi serius, apalagi sanksi terhadap pelaku kekerasan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa tindakan represif dianggap wajar dan dibiarkan.
Ketidakseriusan ini semakin memperburuk citra aparat di mata publik. Bagaimana mungkin aparat yang seharusnya melindungi justru menakut-nakuti tenaga medis? Absennya evaluasi menunjukkan adanya pembiaran sistematis, sebuah indikasi bahwa kekerasan sudah menjadi bagian dari pola kerja dalam penanganan aksi massa.
Kesimpulan
Represifitas aparat terhadap medis adalah tindakan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Medis adalah pihak netral yang hadir demi kemanusiaan, bukan ancaman terhadap keamanan. Dalam setiap aksi, mereka hanya menjalankan tugas mulia: menyelamatkan nyawa manusia.
Namun, fakta menunjukkan bahwa tenaga medis justru menjadi korban. Ambulans dihadang, relawan dipukul, pos medis dirusak, bahkan ada yang diancam akan dibunuh. Semua ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum nasional dan internasional, sekaligus mencederai rasa kemanusiaan.
Sudah saatnya aparat menghentikan praktik represif ini. Pemerintah pun wajib memastikan adanya perlindungan nyata bagi tenaga medis, termasuk menindak tegas aparat yang terbukti melakukan kekerasan. Publik juga perlu ikut mengawasi, agar tragedi serupa tidak lagi terulang.
Represifitas terhadap medis bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika negara serius ingin menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, maka langkah pertama adalah menghormati mereka yang berjuang di garis depan kemanusiaan—tenaga medis.